CERITA DEMOKRASI part 1 (Sejarah perkembangan demokrasi)
Kita semua tau, segala hal yang
menyangkut politik berhubungan erat dengan demokrasi. Tentunya kita paham bahwa
Negara kita menganut sistem demokrasi ala Indonesia, kenapa saya sebut ala
Indonesia, karena jelas demokrasi kita hanya ada di Indonesia, dengan berbagai
fenomena demokrasi yang ada, wajah demokrasi yang penuh intriks, dan segala
macamnya. Inilah demokrasi kawan, yang diagung-agungkan lebih banyak orang
tentangnya. Lantas, tidakkah kita telisik lebih dalam tentangnya. Dari tugas
yang pernah saya dapatkan, saya pun mencari lebih jauh sejenis apa sih
demokrasi yang selalu diperbincangkan itu. Sebelum sampai pada taraf
perbincangan lebih jauh tentang demokrasi, kita akan ulas tentang sejarah
perkembangan demokrasi itu sendiri.
Berbicara
tentang demokrasi, Demokrasi dibagi menjadi dua komponen, yaitu demokrasi
Substansif dan demokrasi prosedural. Komponen pertama adalah landasan normatif
yang bermuatan seperangkat nilai-nilai dasar bagi suatu tatanan (sistem)
kehidupan politik dan ketatanegaraan yang keberadaanya mutlak diperlukan serta
membedakannya dengan sistem yang lain. Komponen kedua adalah seperangkat tata
cara yang dipergunakan agar sistem tersebut dapat bekerja secara optimal dalam
suatu konteks masyarakat tertentu. Jika komponen yang pertama pada hakekatnya
bersifat universal dan permanen, maka komponen kedua bersifat kontekstual
dan bentuknya terus menerus mengalami perkembangan serta terbuka (open-ended).
Menurut Affan Gafar, demokrasi prosedural memiliki beberapa unsur, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen
politik yang terbuka, pemilu dan menikmati hak-hak dasar. Kendati kedua
komponen tersebut tak dapat dipisahkan, namun kedua elemen tersebut dapat
dibedakan satu dari yang lain.
Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi
memberikan jaminan kebebasan yang tak tertandingi oleh sistem politik manapun.
Secara instrumental, demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara. Pertama, pemilu yang bebas dan adil yang secara inheren mensyaratkan hak-hak
politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi, oposisi serta
hak-hak politik mendasar semacam ini tidak mungkin hadir tanpa pengakuan
terhadap kebebasan sipil yang lebih luas. Kedua, demokrasi memaksimalkan
peluang bagi penentuan nasib sendiri, setiap individu hidup di bawah aturan
hukum yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ketiga, demokrasi mendorong
otonomi moral, yakni kemampuan setiap warga negara membuat pilihan-pilihan
normatif dan karenanya pada tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong
kemampuan untuk memerintah sendiri. Selain itu, dalam perkembangannya,
demokrasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase klasik, fase pencerahan, fase
modern, dan fase era kontemporer.
Fase Klasik
Ditandai dengan munculnya
pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar
abad ke 5 SM yang menjadi kebutuhan dari negara-negara kota (city states) di
Yunani, khususnya Athena. Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi
(democratia, dari demos + kratos) disebabkan gagalnya sistem politik yang
dikusai para Tyrants atau autocrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan
terhadap Polis dan perlindungan terhadap warganya. Filsuf-filsuf seperti
Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347SM), Aristoteles
(384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang mengajukan
pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya dikelola sebagai
ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.
Dari buah pikiran merekalah
prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu persamaan (egalitarianism) dan
kebebasan (liberty) individu diperkenalkan dan dianggap sebagai dasar sistem
politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu itu. Tentu saja para
filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap kekuatan dan
kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato,
misalnya, dapat dikatakan sebagai pengritik sistem demokrasi yang paling keras
karena dianggap dapat mendegenerasi dan mendegradasi kualitas sebuah Polis dan
warganya. Kendati Plato mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih
mendukung sebuah sistem politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan
kepada kelompok elite yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan
fisik yang terbaik atau yang dikenal dengan nama “the philosopher Kings”.
Sebaliknya, Aristoteles memandang justru sistem demokrasi yang akan
memberikan kemungkinan Polis berkembang dan bertahan karena para warganya yang
bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan publik,
dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang harus
dipertanggungjawabkan kepada warga.
Demokrasi klasik di Athena, baik dari
dimensi pemikiran dan praksis, jelas bukan sebuah demokrasi yang memenuhi
kriteria sebagai demokrasi substantif, karena pengertian warga (citizens) yang
“egaliter” dan “bebas” pada kenyataannya sangat terbatas. Mereka ini adalah kaum pria yang berusia di atas 20 th, bukan
budak, dan bukan kaum pendatang (imigran). Demikian pula demokrasi
langsung di Athena dimungkinkan karena wilayah dan penduduk yang kecil (60000-80000 orang). Warga yang
benar-benar memiliki hak dan berpartisipasi dalm Polis kurang dari sepertiganya
dan selebihnya adalah para budak, kaum perempuan dan anak-anak, serta pendatang
atau orang asing! Demikian pula, para warga dapat sepenuhnya berkiprah dalam
proses politik karena mereka tidak tergantung secara ekonomi, yang dijalankan
sepenuhnya oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.
Fase
Pencerahan
Pada fase
Pencerahan (Abad 15 sampai awal 18M) yang mengemuka adalah gagasan
alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang dijalankan oleh para raja Eropa
dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini antara lain adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas
Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Montesquieu (1689-1755).
Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep negara yang berdaulat dan
terpisah dari kekuasan eklesiastikal
(Hobbes). Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan sebagai
alternative dari model absolutis.
Pemikiran awal dalam sistem demokrasi
modern ini merupakan buah dari Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak
dominasi Gereja sebagai pemberi legitimasi sistem Monarki Absolut dan
mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem
demokrasi modern, yaitu Revolusi
Amerika (1776) dan Revolusi
Perancis (1789). Revolusi
Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme (James
Madison) sebagai bentuk negara. Revolusi Perancis mengakhiri Monarki Absolut
dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara
universal.
Fase Modern
Fase Modern (awal abad 18-akhir abad 20)
menyaksikan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan
dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas,
nasionalisme, ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dsb. Disamping
itu, terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara
baru sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khusunya
antara kapitalisme dan komunisme.
Pemikir-pemikir demokrasi modern yang
paling berpengaruh termasuk JJ Rousseau
(1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl
Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J.
Schumpeter (1883-1946).
Rousseau
membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana
legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu
apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan dan praktik pembangkangan
sipil (civil disobedience) sebagai
suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran
Rousseau.
Mill
mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty)
yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan
modern (Parliamentary system) di mana
ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi
negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti
pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De Toqcueville juga memberikan kritik
terhadap kecenderungan negara untuk intervensi dalam kehidupan sosial dan
individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang
mandiri.
Marx dan
Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialis-komunis yang
menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung. Negara dianggap
sebagai “panitia eksekutif kaum borjuis” dan alat yang dibuat untuk melakukan
kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih merupakan alat kelas
burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (withering away of the state)
dan digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah
diktator proletariat. Dengan mendasari analisa mereka mengikuti teori
perjuangan kelas dan materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem
demokrasi perwakilan yang diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan
kekuasaan kelas burjuis dan karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (genuine) serta mampu mengartikulasikan
kepentingan kaum proletar.
Max Weber
dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan demokrasi langsung ala
Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan. Mereka berdua
mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam
masyarakat, sesuai dengan roses perubahan masyarakat modern yang semakin
terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Dengan makin berkembangnya birokrasi,
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka tidak
mungkin lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu secara
langsung mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi yang efektif adalah
melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh
karenanya pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.
Fase Era
Kontemporer
Perkembangan pemikiran demokrasi dan
praksisnya pada era kontemporer menjadi semakin kompleks, apalagi dengan
bermunculannya negara-negara bangsa dan pertarungan ideologis yang melahirkan
blok Barat dan Timur, kapitalisme dan sosialisme/komunisme. Demokrasi menjadi
jargon bagi kedua belah pihak dan hampir semua negara dan masyarakat pada abad
keduapuluh, kendatipun variannya sangat besar dan bahkan bertentangan satu
dengan yang lain.
Demokrasi kemudian menjadi alat
legitimasi para penguasa, baik totaliter maupun otoriter di seluruh dunia. Di
negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, pemahaman demokrasi semakin
mengarah kepada aspek prosedural, khususnya tata kelola pemerintahan (governance). Pemikir seperti Robert Dahl umpamanya menyebutkan bahwa teori demokrasi bertujuan
memahami bagaimana warganegara melakukan control terhadap para pemimpinnya.
Dengan demikian focus pemikiran dan teori demokrasi semakin tertuju pada
masalah proses-proses pemilihan umum atau kompetisi partai-partai politik,
kelompok kepentingan, dan pribadi-pribadi tertentu yan memiliki pengaruh
kekuasaan.
Dengan hancurnya blok komunis/sosialis
pada penghujung abad ke duapuluh, demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki
pesaing dan diterima secara global. Fukuyama
bahkan menyebut era paska perang dingin
sebagai Ujung Sejarah (the End of
History) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir.
Pada kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang
cukup pelik karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami
penyesuaian dean tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah
pudar, namun munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah tampil sebagai pemain
dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi liberal.
Kondisi saat ini di mana globalisasi
telah berlangsung, maka demokrasi pun mengalami pengembangan baik pada tataran
pemikiran maupun praktis. Munculnya berbagai pemikiran dan gerakan advokasi
juga menjadi tantangan bagi sistem politik demokrasi liberal, seperti gerakan
feminisme, kaum gay, pembela lingkungan, dsb. Termasuk juga gerakan anti
kapitalisme global yang bukan hanya berideologi kiri, tetapi juga dari kubu
liberal sendiri, semakin menuntut terjadinya terobosan baru dalam pemikiran
tentang demokrasi. Contoh yang dapat disebutkan disini adalah upaya mencari
jalan ke tiga (the Third Way) yang
menggabungkan liberalisme dan populisme di Eropa dan AS.
Mencoba
belajar lebih jauh
Amelia
D’Marthasari
17
Desember 2012
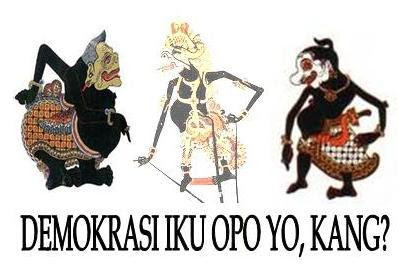


Komentar
Posting Komentar